“November
menjadi bulan kesebelas dari dua belas bulan…”
Buru-buru kuhapus kalimat
itu, lantas berpikir cepat mencari kata-kata baru yang lebih sesuai. Mentok.
Aku menjauhkan diri dari hadapan laptop, melepas kaca mata anti radiasi, lalu
merebahkan diri di kasur kapuk nan empuk. Lagu Obbie Mesakh yang kembali
dipopulerkan oleh Nella Kharisma bergema di penjuru kamarku. Siapa yang
menyetelnya? Aku bertanya-tanya. Lagu itu tidak mengganggu sama sekali, melainkan
liriknya membangkitkan segenap kenanganku.
Aku mulai bernyanyi,
mengikuti alunan musik, hingga sampai di lirik yang menjadi andalannya..
“Jangankan untuk
bertemu
Memandang pun saja
sudah tak boleh
Apalagi
menyanyi bersama bagai hari lalu”
Aku terdiam. Mercerna
beberapa kata-katanya. Kemudian diikuti lirik berikutnya.
“Jangankan mengirim
surat
Menitip salam pun
sudah tak boleh
Ternyata memang kau
tercipta bukan untukku”
Lagu
itu pun usai, aku tertawa, tawa yang tak bisa dijelaskan letak lucunya di
sebelah mana. Kembali ke meja laptop, sembarang menyetel musik, kini lagu Lady
Gaga – I’ll never love again mengalun pelan. Liriknya yang kontras dengan lagu
sebelumnya mampu membuatku tak berkutik. Untuk beberapa saat aku terdiam,
menghayati arti dari lirik tersebut. Sial, terlalu dalam untuk orang yang baru kehilangan.
Aku menarik nafas, mencoba lebih rileks, lantas melanjutkan tulisanku yang
belum separuhnya jadi.
Jakarta
Selatan – Bogor, November 2018.
Dengan
langkah panjang-panjang menuruni JPO, berusaha mengejar waktu sampai di tempat
tujuan. Aku akhirnya sampai di Stasiun terdekat, menempelkan kartu perjalanan
kereta, sejurus kemudian berlari-lari kecil kearah peron stasiun tujuan Bogor.
Terdengar nafas naik-turun, kelelahan. Ular besi pun menepi, menurunkan
sejumlah penumpang, kemudian mengangkut penumpang lainnya, termasuk diriku. Di
dalam kereta, debar dada ini tak bisa dipungkiri, seperti waktu bertemu untuk
kali pertama. Aku mengambil sebuah novel dari dalam tas, usaha menekan rasa
lancang di hati.
Perjalanan
kurang lebih separuh jam itu selesai. Kereta berhenti di stasiun Bogor.
Menjejakan kaki di lingkupi rasa bahagia. Sebelumnya, aku hendak ke kamar
mandi, mematut diri, merapikan setelan pakaianku yang sedikit lecak di salah
satu sisi. Lalu, bergegas mengunjungi sebuah taman di sekitaran Kebun Raya
Bogor. Di taman itulah, tepatnya di undakan paling atas aku terduduk. Sendiri.
Di
bawah pohon rindang, terpaan sinar matahari yang jatuh melewati celah-celah
ranting, aroma petrichor, dan sebagai pelengkap kesiur angin. Aku menyukai
tempat ini, meski tanpa ditemani siapa pun. Saat itu yang tertanam dalam otakku
adalah “Menulislah, menulislah”.
“Apa
yang kau lakukan seorang diri di sini?”
Aku
mengangkat kepala, menatap lurus.
“Aku
sedang mencari inspirasi”
Lengang,
hanya daun kering yang berguling-guling diterpa angin.
“Yakin
hanya itu? tidak ada yang lainnya”
Pertanyaan
itu sungguh mengusik. Aku hendak menjawab, namun sesuatu menahanku.
“Katakan
saja, tak akan ada yang membocorkannya”
“Baiklah,
aku akan jujur.”
“Jawablah
pertanyaanku sebelumnya”
“Di
sini, di taman ini, aku…aku..”
Suaranya
hilang begitu saja.
“Iya,
kau kenapa?”
Menanti
jawaban.
“Aku,
kan sudah kubilang aku mencari inspirasi untuk menulis di sini, di taman ini,
latar tempatnya sesuai dengan jalan cerita yang kubuat”
“Hmm”
“Kau
masih berkomunikasi dengannya?
“Dengan
siapa?”
“Jangan
mengelabui dirimu sendiri”
Terdengar
tarikan nafas tertahan.
“Masih.”
“Kenapa?”
“Aku
hanya ingin menjadi seutuhnya, bukan sebutuhnya”
“Oh,
dia memperlakukanmu sebutuhnya?”
Memejamkan
mata.
“Aku
tak bisa menjawabnya”
“Kau
bisa, hanya saja tidak terlalu berani”
Aku
meremas kertas tulisanku sekuatnya, sampai terlihat lecak di sana-sini.
“Lihatlah,
tanpa kau berbicara gesturmu sudah menunjukkan jawabannya.
Aku
lagi-lagi menunduk.
“Kau
juga menulis untuknya kan”
Kali
ini dia tersenyum.
“Iya,
aku menulis tentangnya”
“Bukankah
dia tak suka membaca?”
“Memang.”
“Lalu,
untuk apa capek-capek menulis untuk suatu karya yang tidak dihargai”
“Aku
pelupa, dengan menulis, aku mengabadikannya.”
“Alasan”
Lengang.
“Apa
kau masih mengharapkannya hadir di sini…”
“Iya
dan tidak, untuk beberapa hal, aku lebih baik mundur perlahan, mencari jalan
lain”
Lihatlah
kedua matanya mengembun.
“Kau
menangis?”
“Tidak”
“Tak
apa, keluarkan saja”
Aku
mengambil selembar tissue, menahan lelehan air mata.
Terdengar
sesenggukan kecil.
“Kau
pasti sedang merindukannya kan, sampai rela jauh-jauh ke taman ini”
Lagi-lagi
pertanyaan itu menggaung.
“Aku
ke taman ini pertama, untuk mencari ide menulis seperti yang kukatakan tadi, ya
sekalian menghirup udara sejuk. Kedua, aku di taman ini sedang menapak tilas
tentang apa yang pernah terjadi di sini, di taman ini.
Tak
ada keraguan dalam tutur katanya, mantap.
“Tapi
kau merindukannya bukan?”
Ah,
pertanyaan itu.
“Ya,
aku memang merindukannya, ta…tapi aku sadar, a…aku…”
Kalimatnya
terpotong, hening.
“Sudah
kau tak perlu lagi menjawabnya, kedua matamu sudah berbicara jujur sedari awal”
Aku
tertawa, tersipu malu mengakuinya.
“Sekarang,
mengapa kau tak memberi kabar padanya bahwa kau sering mampir ke taman ini?”
“Aku
hanya tidak mau mengganggunya lagi”
“Gengsi.”
Senyap.
“Benarkan
kau gengsi menghubunginya duluan?”
Matanya
mengerjap-ngerjap.
“Untuk
apa aku gengsi dalam hal yang berkaitan dengan hati? Untuk apa? Aku lebih baik
mengutarakan kepadanya, terserah dia mau mengganggap aku ini apa, terserah.
Yang penting aku lega!”
Dia
terlihat berapi-api, tapi di akhiri senyum mengembang.
“Kalau
dia membaca tulisanmu ini, apa yang ingin kau katakan padanya?”
Hening.
Dia
terlihat memikirkan sesuatu.
Satu
menit.
Lima
menit berlalu.
Nafasnya
terasa lebih berat.
“Aku
hanya ingin mengatakan…”
Bersambung…
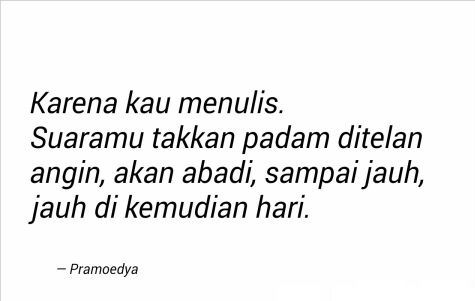

Tidak ada komentar:
Posting Komentar